Diskursus tentang ilmu tampaknya begitu fundamental sekaligus lumayan mainstream. Kita semua mungkin sudah sangat sering menemui pembahasan tentang ilmu dari berbagai sudut pandang.
Dahulu semasa saya masih duduk di bangku MI, kutipan yang paling sering saya dengar adalah, “Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina!”. Kutipan tersebut dulu diklaim sebagai hadis Nabi saw, yang lantas melahirkan pertanyaan, “Mengapa Nabi saw dalam hadis tersebut menyebut Cina, bukan negeri lain?”.
Namun, dalam buku “Hadis-hadis Bermasalah” karangan Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub, MA disebutkan bahwa Imam Ahmad ibn Hanbal menentang pendapat yang mengklaim kutipan tersebut adalah sebuah hadis Nabi saw.
Terlepas dari hal di atas, proses mencari ilmu itu sebenarnya berlangsung hingga akhir hayat. Dengan kata lain, mencari ilmu itu bukan semata belajar di dalam kelas, melainkan belajar di setiap hembusan napas. Selain itu, kegiatan mencari ilmu juga nggak bisa jika hanya dilakukan di satu tempat (wilayah).
Kita harus pergi ke tempat lain supaya menemukan sudut pandang baru dan pemahaman yang lebih luas. Sebagai contoh, dalam menempuh pendidikan dari Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi nyatanya kita berpindah-pindah lokasi. “Loh!? Itu kan emang udah diatur sistem”. Oke! Kita cari contoh lain.
Mundur jauh ke belakang, mari kita lirik sejenak perjalanan intelektual Imam al-Ghazali. Dari situ kita akan menemukan fakta bahwa beliau nggak cuma mencari ilmu di satu tempat.
Sebenarnya, al-Qur’an sendiri telah menyinggung tentang hal ini. Mari lihat surat al-Taubah ayat 122 yang terjemahnya kurang lebih begini, “Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya”.
Bila dikaitkan dengan hadis tentang niat, barangkali aktivitas mencari ilmu bisa terwakilkan dalam slogan ni, “Di mana kaki dipijakkan, di situ niat mencari ilmu diikrarkan”. Oh, iya! Karena tema kali ini ilmu, mohon dimaklumi ya kalo tulisannya terasa seperti berdakwah.
Mungkin kita pernah mengalami fase sekularisasi ilmu, fase di mana kita berpandangan bahwa ilmu agama dan sains adalah dua entitas yang berbeda dan tidak pernah bisa bersama. Kita berdebat, membenturkan argumen tentang ilmu mana yang lebih utama untuk dipelajari.
Namun, beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan artikel yang mengubah sudut pandang saya terkait hal ini. Artikel tersebut memaparkan contoh beberapa cendekiawan muslim terdahulu yang menghafal al-Qur’an saat masih kecil dan mempelajari sains saat dewasa.
Berangkat dari hal tersebutlah saya akhirnya berhenti bertanya-tanya mana yang lebih baik antara ilmu agama dengan sains. Selain itu, standar ‘manusia terbaik’ menurut Nabi saw itu sangat sederhana, yakni manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya.
Bicara soal manfaat, ada satu istilah yang tentu sudah nggak asing di telinga, yakni ‘ilmu yang bermanfaat’. Istilah tersebut sepertinya banyak dikenal sebab hadis Nabi saw yang menjelaskan tentang 3 perkara yang tidak akan terputus pahalanya hingga yaum al-akhir. Ia meliputi sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak terhadap orang tuanya.
Dahulu para guru mata pelajaran al-Qur’an dan Hadis bilang kalo contoh dari ‘ilmu yang bermanfaat’ itu begini, “Misal kita merupakan orang yang pertama mengajarkan basmalah pada satu orang. Di waktu yang lain, orang tadi ternyata mengajarkan basmalah ke orang lainnya. Dalam kasus ini, kita sebagai pengajar pertama akan tetap mendapat pahala meski sudah nggak mengajarkannya”.
Sayangnya, beberapa orang masih menelan contoh tersebut apa adanya tanpa memerhatikan konteks realitas sosial. Akibatnya apa? Mereka beranggapan bahwa orang yang memiliki ilmu yangb bermanfaat hanya guru, ustaz, atau kiyai. Musababnya karena merekalah pihak yang melakukan hal yang sama dengan contoh kasus ‘ilmu yang bermanfaat’ tadi.
Padahal sebenarnya konteks ilmu yang bermanfaat itu lebih luas dari sekadar ‘mengajarkan’. Sependek yang saya lihat, setiap ilmu itu pasti bermanfaat. Namun, praktiknya jelas nggak seragam.
Contoh, orang yang kuliah di fakultas kedokteran tentu nggak mungkin mengajarkan ilmunya pada orang awam. Tugas mereka adalah mengobati orang yang sakit. Lantas, apa mereka langsung dicap ilmunya nggak bermanfaat? Ya nggak bisa lah, enak aja!. Ilmu mereka tetap bermanfaat, tapi dengan jalan yang berbeda.
Saya pernah bertemu dengan penceramah yang agak ‘radikal’ pemahamannya tentang ilmu yang bermanfaat ini. Orang ini pernah berkata, “Lebih baik memiliki ilmu yang sedikit tapi bermanfaat, daripada punya ilmu banyak tapi nggak bermanfaat”.
Orang ini termasuk orang yang beranggapan bahwa kemanfaatan sebuah ilmu itu ya diajarkan. Saya rasa ada 2 hal yang agak janggal dari pernyataan penceramah tersebut. Pertama, ia seolah merasa dirinyalah yang ilmunya paling bermanfaat, dengan dalih karena ia menjadi seorang penceramah. Ini tentu merupakan satu bentuk penyempitan makna ‘ilmu yang bermanfaat’ yang sedikit dibumbui rasa bangga diri.
Kedua, pernyataan penceramah tadi terasa seperti mengandung unsur legitimasi kebodohan. Penyebutan ‘ilmu yang sedikit’ menjadi indikasi bahwa penceramah tersebut enggan untuk menambah ilmunya.
Hal ini sangat kontradiktif dengan apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abu Basyir al-Romawiy dalam kitab “Alaalaa Tanaal al-‘Ilm illaa bi Sittah”. Beliau menulis yang terjemahnya kurang lebih begini, “Orang berilmu yang nggak melakukan ibadah merupakan satu bentuk kerusakan yang besar. Akan tetapi, orang bodoh yang ngeyel menjalankan ibadah (dengan kebodohannya tersebut) justru menjadi sutau kerusakan yang lebih besar lagi”.
Dari ungkapan tersebut kita akhirnya mafhum bahwa orang yang berilmu selalu memiliki derajat yang lebih tinggi daripada orang yang bodoh. Jadi…..buat yang merasa ilmunya masih sedikit kayak saya contohnya; please, lah! Jangan malah berbangga diri!
Justru hal tersebut harus menjadi pemicu supaya kita tetap semangat belajar dan mencari ilmu. Perkara ilmunya nanti bermanfaat atau nggak, saya rasa akan tetap bermanfaat. Jika belum bermanfaat buat khalayak luas, setidaknya bermanfaat untuk diri sendiri. Terakhir! Yok stop mempersempit makna ‘ilmu yang bermanfaat’.
Editor: Ciqa
Gambar : Pexels


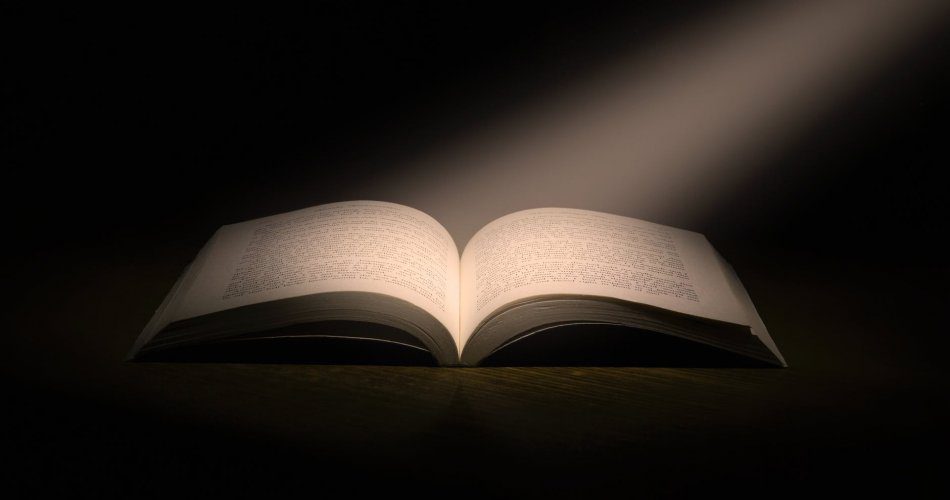
Comments