Apakah memakai Twitter sejak 2 tahun lalu bisa disebut ‘anak lama’? Hmm, entahlah. Agaknya terlalu dini mengatakannya dengan dasar sering log in. Terlepas dari itu, tanpa mengklaim sebagai anak lama, Twitter dan saya punya cerita tersendiri terkait dengan fitur retweet belakangan ini. Bisa dibilang, retweet adalah star syndrome ringan.
Retweet adalah Star Syndrome Ringan
Singkat saja, saya akhir-akhir ini sedikit resah dengan fitur retweet di Twitter. Sejujurnya, ada keresahan pada media sosial secara umum. Ini berawal setelah saya menonton video di kanal Youtube Deddy Corbuzier yang berbincang dengan Nadiem Makarim. Yap, Bapak Mendikbud RI. Dari pembicaraan ngalor-ngidul yang berjalan sekitar 30-an menit, saya paling memperhatikan bahasan media sosial. Poin pentingnya adalah, penggunaan media sosial yang awalnya adalah ruang berbagi, kini berubah menjadi ruang rekognisi sosial. Akhirnya, terjadilah gangguan pada kesehatan mental. Dan ini terjadi secara massal.
Sebagai pengguna di berbagai medsos, saya jelas merasa tersentil. Ada beberapa gangguan yang pernah saya alami. Dalam konteks Instagram, Bang Nadiem bilang kebiasaan seperti pikir jero buat upload dan ngitungin jumlah likes itu tidak baik buat kesehatan mental. Kalaupun saya masukkan ke dalam konteks Twitter, tentu akan sangat bersinggungan dengan fitur retweet. Pahitnya, saya masih merasakan gangguan itu hingga sekarang.
Retweet menurut saya adalah fitur yang adiktif. Kata-kata bijak atau hal paling relate dengan kehidupan adalah modal yang cukup meyakinkan untuk mempertebal pengakuan sosial. Dengan itu, para pengikut seolah-olah mengakui apa yang Anda bilang itu benar dan sangat relatable. Lalu, mereka mengulangi perkataan anda agar orang lain juga tahu bahwa Anda sedang membicarakan hal yang sangat penting dan perlu khalayak ketahui. Kemudian, Anda dapatkan pengakuan itu sebagai buah tweet Anda, dan akan terus melakukannya lagi hingga akhirnya sadar bahwa itu bikin kecanduan. Ya, analogi yang belibet tapi intinya seperti itu.
Saya katakan star syndrome ringan karena angka retweet menumbuhkan kebanggaan tersendiri, meskipun dosisnya sangat kecil. Ibarat seorang seniman, memproduksi atau memamerkan karya seninya pasti adalah kebanggaan.
Namun, jika menyikapinya dengan berlebihan hingga merasa ‘sok hebat’ dan terlampau jumawa, tentu terlihat tidak baik. Saya menganggap desiran rasa bangga tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Namun, perasaan tersebut harus dikontrol agar tidak bikin lupa diri dan menjadi candu.
***
Tidak ada maksud saya untuk menggeneralisasi. Ini murni apa yang saya rasakan. Toh, penggunaan fitur retweet bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kalaupun mengalami hal yang sama, semoga kita sama-sama bisa kembali seperti semula.
Editor: Nabhan


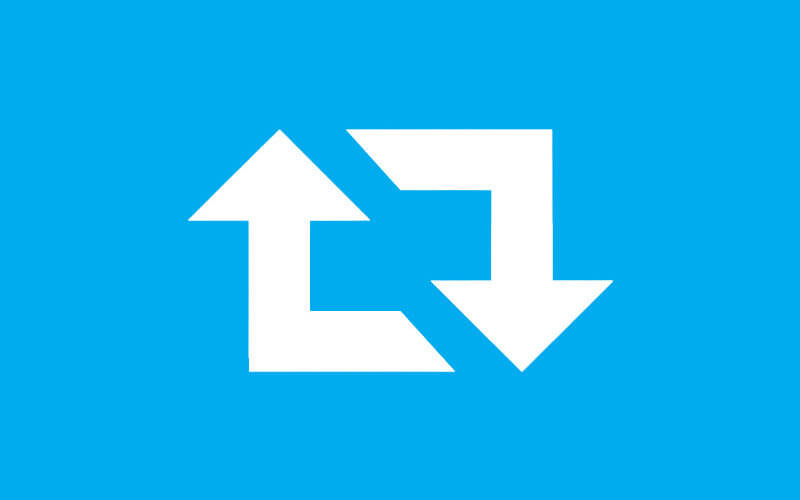
Comments