Menjadi seorang mahasiswa adalah profesi paling agung di kalangan orang yang sedang mencari ilmu. Bagaimana tidak? Jika ditelaah secara harfiah pun sudah terlihat, bahwa mahasiswa adalah orang yang belajar di taraf lembaga pendidikan tertinggi.
Dari sekian banyaknya anak muda di Indonesia yang mencari ilmu, tak semuanya bisa mengenyam profesi tersebut. Sebuah profesi yang dalam praktiknya diatur sekonservatif mungkin, mengikuti struktur metodologi dan aturan-aturan etis, untuk bisa tiba pada kompetensi ilmu yang hendak dipelajari.
Tapi, semua formalitas itu menurut saya tampaknya tak akan berarti, bila seorang mahasiswa masih berada di iklim feodalisme kampus. Lantas, apakah feodalisme? Mengapa mahasiswa bisa berada di iklim feodalisme kampus? Dan, apakah sebegitu riskannya feodalisme menggempur kegiatan mahasiswa dalam mencari ilmu?
Kalau kita sedikit minggir dari ranah sosial politik, feodalisme adalah sebuah sistem yang memberikan kekuasaan besar pada pihak tertinggi dan mengangung-agungkan jabatan dari pihak tersebut.
Iklim Feodalisme Kampus
Atau lebih sederhana dan konkretnya, kita sebagai mahasiswa pasti tak jarang menemui sikap yang hanya berucap, “iya, Bu. Iya, Pak. Terima kasih, Bu. Sudah cukup, Pak. Mohon maaf, Bu. Mohon maaf, Pak.” sembari tidak lepas dengan emot high five ketika perkuliahan online berlangsung.
Semua itu menurut saya adalah wujud dari sistem feodalisme kampus. Di mana seseorang layaknya robot, yang hanya manut, manut, dan manut ketika diberi sebuah penjelasan tanpa adanya pertimbangan pikiran.
Di sisi yang lain, tentu menjadi suatu hal yang pasti juga, bila memang sebuah penjelasan sudah benar-benar layak untuk diterima secara akal sehat. Akan tetapi, yang dimaksudkan di sini adalah bukan berarti segala apapun yang telah dipaparkan oleh seorang dosen, lantas semuanya bisa ditelan secara impulsif.
Apa kemudian yang menjadi landasan jika segala hal yang keluar dari pikiran dosen adalah sebuah absolutely kebenaran. Apakah karena beliau menyandang identitas dosen? Sehingga kita menyimpulkannya kalau dosen yang berbicara, maka semuanya adalah kebenaran?
Bagaimana kalau seumpama dosen menyuruh untuk mencuri kotak amal masjid, apakah kita akan mengiyakan? Tentu tidak, kan. Kecuali kalau menyuruh untuk mencuri hati seseorang, tak perlu disuruh pun kalian akan melakukan.
Kalau logika yang dipakai dalam perkuliahan bercorak feodal, harusnya kita tak perlu repot-repot menyandang profesi mahasiswa. Tak perlu susah-payah orang tua membiayai kita berjuta-juta bahkan sampai puluhan juta kalau hanya untuk kita cosplay sebagai robot.
Apa bedanya kalau begitu kita mencari ilmu di kampus, dengan mencari ilmu di warung kopi bersumber google ditemani kopi seharga tiga ribu.
Menghidupkan Budaya Kritis
Di dalam kampus, selain tersedianya struktur mata ilmu dan kesahihan metodologi, juga karena sudah tersedianya ruang diskusi dengan orang yang kompeten di bidang ilmu tersebut.
Bisa saling bertukar pikiran, mempertanyakan yang belum jelas, sampai bahkan bisa saling bantah dengan seseorang yang sudah terlegitimasi kompetensi keilmuannya.
Perihal mempertanyakan, mendiskusikan, atau bahkan membantah penjelasan dosen memang kerapkali dianggap sebagai sebuah sikap yang melanggar etika. Menurut saya, banyak sekali miss-persepsi tentang hal ini.
Dengan mendayagunakan akal kita, bukan berarti kita tidak memiliki etika terhadap dosen. Justru malah di situ kita memiliki etika yang lebih luas.
Satu sisi kita menganggap dosen sebagai manusia biasa yang pasti bisa saja salah, di sisi lain kita juga beretika terhadap Tuhan yang telah memberikan kita akal.
Kalau kita sikapnya manut dan seakan dosen dianggap sebagai maha benar, maka harusnya di sinilah letak kita tidak beretika. Sudah diberi keistimewaan berupa akal, kok malah digunakan untuk memunafikan manfaatnya, dan mencitrakan manusia seperti Tuhan.
Etika Berdiskusi
Tentu dalam berdiskusi bukan berarti kita harus buta dengan norma-norma kemanusiaan. Apalagi dengan seorang yang lebih tua dibandingkan kita.
Penggunaan bahasa dan tingkah laku juga perlu kita perhatikan dalam berdiskusi. Jangan sampai yang awalnya diskusi berharap menambah pengetahuan, lantas berakhir menjadi perseteruan.
Lagi pula, diskusi, bertanya, atau membantah, bagi saya adalah ditujukan pada apa yang disampaikan, bukan pada siapa yang menyampaikan.
Jadi, tak ada soal bila bertukar pikiran itu dianggap hal yang melanggar etika. Sebab, bertukar pikiran adalah kegiatan yang bersentuhan dengan argumen, bukan kegiatan yang bersentuhan dengan sentimen.
Kalau dalam perkuliahan ihwal bertukar pikiran dianggap bersentuhan dengan sentimen, maka harusnya diganti saja konsep “perkuliahan” itu dengan konsep “pergosipan”.
Asal Mula Iklim Feodal
Lantas, apakah yang menyebabkan seorang mahasiswa nyaman berada di iklim feodalisme kampus? Apakah karena adanya sikap otoriter dari seorang dosen?
Tentu saja tidak. Malahan, hampir semua dosen selalu menawarkan mahasiswanya untuk berdiskusi dan bertanya.
Sejauh yang saya tahu, inti dari alasan mengapa mahasiswa nyaman belajar di iklim feodal adalah karena tidak adanya rasa kebutuhan dalam dirinya.
Maksudnya ialah mahasiswa belum menemukan sebuah kebutuhan di dalam ilmu pengetahuan yang ia tekuni, belum menemukan apa yang penting dari ilmu tersebut bagi keberadaan dirinya.
Sehingga ketika di dalam perkuliahan, mereka hanya bersikap manut meskipun belum paham.
Hal ini saya kira juga didukung dengan sebuah pernyataan dari seorang psikolog humanistik asal Amerika. Mahasiswa psikologi pasti tak asing dengan nama Abraham Maslow.
Beliau pernah mengatakan bahwa kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan seseorang untuk mampu menjadi apa yang diinginkan sesuai dengan potensi yang dimiliki.
Dalam perkataan beliau tersebut, saya menginterpretasikan bahwa manusia itu akan beraktual ketika dirinya menemukan sesuatu yang ia anggap sebagai kebutuhan aktualnya.
Misalnya saja kalian sedang kasmaran dengan seseorang. Lantas, kalian ingin berpacaran dengan dia. Kalian pasti akan melakukan segala cara agar bisa mendapatkan hatinya.
Entah itu dengan mengubah penampilan, memperbaiki fisik, atau chatting dengan dia terus-terusan. Nah, contoh berpacaran disini yang disebut kebutuhan aktualisasi diri.
Sama halnya ketika dalam perkuliahan. Seorang mahasiswa harusnya punya kebutuhan aktualisasi mengenai ilmu yang tengah ia pelajari.
Ketika merasa belum paham atau tidak sependapat dengan yang disampaikan oleh dosen, harusnya mahasiswa melakukan segala cara untuk bisa paham dan sependapat dengan ilmu yang disampaikan dosen.
Kebutuhan Mahasiswa
Kebutuhan daripada seorang mahasiswa adalah mempunyai ilmu yang kompeten.
Tapi, kalau pun kompetensi ilmu itu tidak dijadikan sebagai kebutuhan, lantas apa yang mahasiswa butuhkan?
Apakah ijazah? Kalau memang begitu, berarti diganti saja terminologi dari mahasiswa. Bukan lagi seseorang yang mencari ilmu di perguruan tinggi. Tapi seseorang yang mencari secarik kertas agar citra dirinya terlihat tinggi.
Pola pikir feodal ini tak hanya berpengaruh pada sistem belajar mahasiswa. Menurut saya, bila seseorang yang ketika diberi penjelasan hanya mengiyakan karena yang memberi penjelasan adalah orang yang punya identitas tertinggi.
Maka, kedepannya stimulus kita sangat mungkin gampang menerima sebuah dogma. Di sini perihal dogma bukan berarti menegasikan agama, ya.
Tapi, yang dimaksud adalah aliran-aliran radikal seperti dogma terorisme, motivasi dari pengusaha gadungan, ataupun ucapan manis dari seorang yang tidak baik.
Kita akan lebih gampang menerima omongan dengan melihat siapa yang bicara, bukan apa yang dibicarakan. Dan dampaknya, kita akan selalu mengikuti omongan orang, tanpa peduli dengan keaslian diri kita.
Lagi-lagi dalam hal ini juga relevan seperti yang pernah diucapkan oleh seorang tokoh. Kali ini dari seorang psikolog Pendidikan asal Amerika, Edward Lee Thorndike.
Dalam buku The Art of Thinking Clearly karya Rolf Dobelli yang memaparkan salah satu bias mental sekitar hampir seratus tahun yang lalu. Nama bias itu adalah efek silau atau hallo effect.
Sederhananya, bahwa satu ciri (misalnya kecantikan, status sosial, usia) menghasilkan kesan positif atau negatif yang bersinar melebihi yang lain, dan menyebabkan efek keseluruhannya tidak seimbang.
Dengan begitu, saya pikir sangat korelatif dengan dampak dari pola pikir feodal ini. Saking besar dan tingginya identitas dosen yang bersinar, sampai-sampai apa yang disampaikan oleh dosen menjadi tidak terlihat karena silaunya sinar identitas dari seorang dosen.
Dengan harapan lebih, semoga kawan-kawan seperjuangan segera menyadari bahayanya iklim feodal ini. Kasihan dengan orang tua, pun sungkan dengan Tuhan. Masak iya, kita ini diciptakan di situasi berpendidikan hanya untuk memunafikan keistimewaan kita?
Editor: Lail
Gambar: Pexels


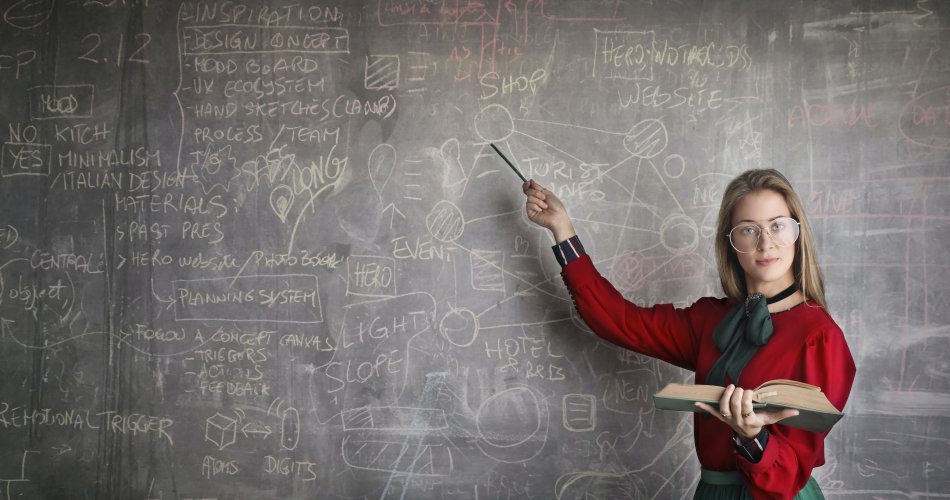
Comments